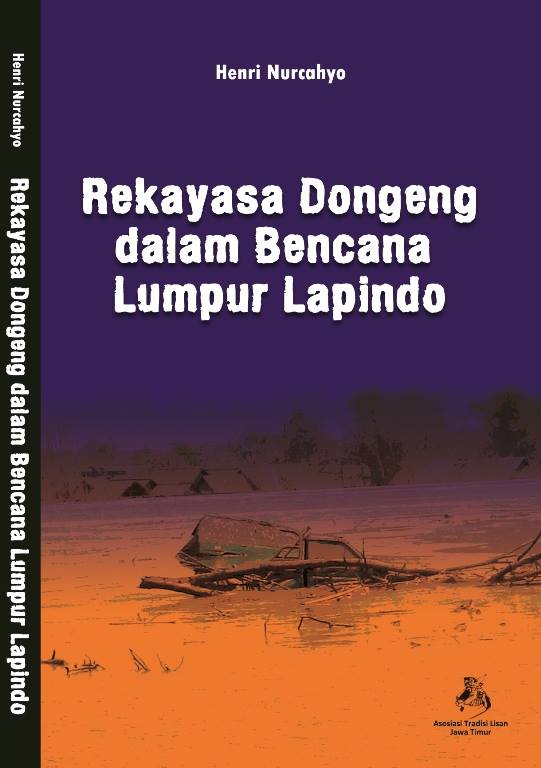Artikel ini adalah versi asli dari yang dimuat di Jawa Pos, Minggu 5 Januari 2014 (versi PDF)
 Judul Buku : Rekayasa Dongeng dalam Bencana Lumpur Lapindo
Judul Buku : Rekayasa Dongeng dalam Bencana Lumpur Lapindo
Penulis : Henri Nurcahyo
Penerbit : Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Timur
Tahun : 2014
Halaman : vi + 210 halaman
Peresensi : Anton Novenanto. Dosen pada Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya, Malang
Sejak lahirnya, 29 Mei 2006, lumpur panas di Porong, Sidoarjo telah menjadi suatu arena pertarungan kuasa yang mahadahsyat. Sampai saat ini, pertarungan kuasa mengerucut pada dua kubu utama: kubu bencana alam dan kubu bencana industri. Indikasi keberadaan dua kubu dapat dilihat dengan mudah dari nama yang digunakan. Para aktor kubu bencana alam akan menggunakan terminologi “lumpur Sidoarjo”, atau Lusi; sementara aktor pada kubu bencana industri bersikeras menggunakan istilah “lumpur Lapindo”.
Dari sini, kita pun dapat membaca kecenderungan Henri Nurcahyo dalam buku terbarunya berjudul: Rekayasa Dongeng dalam Bencana Lumpur Lapindo (selanjutnya, Rekayasa Dongeng). Henri berada pada kubu bencana industri.
Permasalahan utama yang diangkat dalam Rekayasa Dongeng adalah bagaimana folklore, atau cerita rakyat yang diwariskan secara lisan, dipergunakan dalam pertarungan kuasa terkait kasus Lapindo ini. Rekayasa Dongeng merupakan respons dari usaha seorang geolog, Awang Harun Satyana, yang menggunakan dongeng Timun Mas untuk menunjukkan bahwa semburan lumpur di Porong itu hanyalah gejala alam belaka.
Tentu saja, pencarian kebenaran dengan mengkaitkan dongeng Timun Mas dengan kondisi ekologis (danau lumpur) di dunia nyata, seperti yang dilakukan Awang, merupakan bukti bahwa dongeng berfungsi sebagai wacana. Usaha semacam ini merupakan ironi karena dilakukan oleh seorang geolog, yang idealnya menyusun argumen berdasarkan data-data yang metodologis, yang ilmiah, bukan dari sebuah dongeng.
Henri berpendapat, lumpur Lapindo dan folklor Timun Mas adalah dua entitas berbeda. Satu-satunya keterhubungan antara keduanya adalah “kebetulan [dongeng Timun Mas] juga menyebut mengenai danau lumpur sebagaimana yang terjadi di Porong sekarang ini” (3), meskipun begitu sebuah dongeng berangkat dari “fakta yang sudah ada sebelumnya” (18). Oleh karenanya, keberadaan danau lumpur dalam dongeng Timun Mas menggelitik untuk ditelusuri lebih dalam.
Bagi Henri, setiap cerita rakyat mengandung kearifan lokal yang dapat digali dengan mencari makna dari simbol yang dimunculkan. Henri melihat bahwa dalam folklor Timun Mas tersimpan pesan moral tentang bagaimana relasi negara (raksasa) dan rakyat (Timun Mas) (43-47). Ada dua pesan yang hendak disampaikan. Pertama, pesan pada pengelola negara agar tidak semena-mena pada rakyatnya dan meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh rakyatnya. Kedua, pesan pada rakyat agar tidak mudah menyerah dengan kondisi yang ada.
Dalam Bab 11 (Kontroversi Dongeng Timun Mas), Henri mengungkapkan pelbagai versi dongeng Timun Mas dalam masyarakat dan tidak semuanya menyebut tentang danau lumpur. Hal ini memperjelas tesis bahwa dongeng Timun Mas, yang menyebutkan danau lumpur, telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk memenangi pertarungan kuasa, pencarian kebenaran dalam kasus Lapindo.
Inilah yang menarik dari Rekayasa Dongeng. Titik beratnya bukanlah pada mencari “kebenaran” di balik sebuah dongeng, melainkan bagaimana sebuah dongeng berfungsi sebagai salah satu “wacana” dalam arena pertarungan kuasa pencarian kebenaran. Di sinilah tesis utama Rekayasa Dongeng, tentang bagaimana selama ini dongeng Timun Mas telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk mendukung pendapat salah satu kubu (kubu bencana alam) adalah sesuatu yang problematik.
Selama ini kasus Lapindo lebih banyak dikaji dari aspek geologis, hukum, politik ekonomi, gerakan sosial, media massa, planologi, ataupun psikologis. Nyaris tidak ada penulis yang menggunakan pendekatan budaya untuk mengkaji kasus Lapindo. Jika betul demikian, maka Henri adalah pionir.
Penulisan dan penerbitan Rekayasa Dongeng merupakan bukti nyata bahwa pertarungan kuasa, pencarian kebenaran, atas kasus Lapindo masih terus bergulir, masih belum tuntas. Rekayasa Dongeng melampaui dari apa yang ditulis Ayu Sutarto dalam pengantarnya sebagai “laporan jurnalistik yang bernuansa folkloristik dan historik” (16). Rekayasa Dongeng, menurut saya, justru menghidupkan dan menghidupi arena pertarungan kuasa seputar kasus Lapindo.
Dengan menawarkan gagasan tentang bagaimana kubu “bencana alam” telah menggunakan fitur-fitur budaya, dongeng, sebagai “amunisi” dalam pertarungan kuasa atas Kasus Lapindo, Henri telah membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan rekonstruksi, bahkan dekonstruksi atas segala narasi budaya tentang bencana lumpur panas tersebut.
Dengan kata lain, Rekayasa Dongeng merupakan salah satu wacana penting bagi siapapun yang hendak, sedang, dan pernah mendalami kasus Lapindo.