Kehidupan sosial budaya korban Lapindo remuk sudah, lahir dan batin. Ikatan kekerabatan hancur, yang berakibat semakin rentannya kehidupan sehari-hari. Begitu pula, tradisi dan budaya tak bisa lagi dijalankan, yang lalu berefek hilangnya kekuatan batin, lenyapnya ingatan bersama, yang telah lama menjadi daya tahan ampuh dalam menghadapi kerasnya hidup.
Tanyalah Mbok Lina, dia akan tahu bagaimana hidupnya berubah begitu kekerabatan dan kehidupan komunal itu lenyap. Sore itu, di pengungsian Pasar Porong Baru, Mbok Lina (65), sedang membersihkan kulit buluh bambu, sendiri. “Buat gedek, mau bikin gubuk nanti kalau sudah pindah,” ujarnya. Bersama sekitar 500 keluarga dari Desa Renokenongo, Mbok Lina nanti akan pindah kalau sudah memperoleh uang ganti rugi. Dia menyiapkan sendiri bambu-bambu itu.
Dulu, sewaktu di Dusun Sengon, Desa Renokenongo, Mbok Lina merasa berbagai persoalan hidup lebih ringan, karena ada kebersamaan, saling membantu. Mbok Lina hidup juga dari adanya solidaritas yang terbangun puluhan tahun ini. Dia mengerjakan sawah milik tetangga. “Dulu iso nggarap sawah Haji Sarim, Haji Daelan, Haji Karyo. Tak kurang haji-haji di Sengon punya sawah yang bisa digarap,” kenang Mbok Lina.
Mbok Lina dulu bisa mengerjakan banyak hal di sawah tetangga-tetangga itu. “Ya tanam, membersihkan rumput dari padi, juga panen.” Dari kampung Mbok Lina, sedikitnya ada enam orang yang turut bekerja di sawah bersamanya.
Kini semua lenyap. Beberapa nama orang yang dulu sering memberi bantuan pekerjaan, diceritakannya meninggal beberapa waktu setelah lumpur meleduk. “Sakit-sakitan memikirkan (krisis) Lapindo ini,” kata Mbok Lina. Kalaupun tidak, mereka ini juga sudah tidak lagi mampu membeli sawah karena belum selesai pembayaran ganti rugi kepada mereka. Mbok Lina menyebut salah seorang ahli waris yang sudah membeli sawah di kawasan Tulangan, Sidoarjo.
Toh, Mbok Lina tidak bisa ikut membantu mengerjakan sawah di sana. “Nggak begitu kenal sama anaknya,” begitu alasan Mbok Lina. Tentu saja memang tidak mudah membentuk lagi kebersamaan warga seperti dulu. Perasaan saling kenal dan tepo seliro bukan hal yang bisa muncul begitu saja dalam semalam.
Sekarang, Mbok Lina hanya menggantungkan hidup dari pemberian lima orang anaknya: Buarin, Mulyono, Roibah, Sriasih, dan Narto. Tapi anak-anaknya telah hidup sendiri-sendiri. Praktis, Mbok Lina hanya tinggal hidup berdua dengan suaminya Senawan (70) yang telah sakit-sakitan. “Sejak pindah ke pasar (pengungsian), dia sakit, kepikiran rumahnya yeng tenggelam.”
Untuk pembiayaan suaminya, Mbok Lina sudah mengeluarkan biaya tidak kurang dari dua juta rupiah, jumlah uang yang tidak sedikit bagi seorang tua yang telah kehilangan rumah dan tidak punya penghasilan itu. Dari anak-anaknya, Mbok Lina mengaku diberi uang seminggu sekali rata-rata sekitar 30 ribu rupiah. “Itu pun kalau sudah dapat gaji.” Dengan uang sebesar itu, Mbok Lina dan suaminya harus menyiasati menyambung hidupnya.
Bila nanti benar-benar harus keluar dari Pasar Porong Baru dan memulai hidup dengan uang kompensasi seadanya, Mbok Lina tidak tahu apakah di tempatnya yang baru bisa kembali bekerja di sawah. Dia jelas tidak tahu karakteristik orang-orang di tempatnya yang baru nanti. Menurut rencana, komunitas warga Renokenongo ini akan pindah ke wilayah Desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung, sebuah daerah di sebelah barat Kecamatan Porong di sisi utara aliran Kali Porong. “Yo embuh, semoga tetangga-tetangga nanti di sana pengertian, tepo seliro,” ujar Mbok Lina, lirih.
Jika Mbok Lina merasakan betul kehidupan lahirnya berantakan lantaran ikatan komunitas telah dihancurkan Lapindo, Nawawi tahu rasanya kehidupan batin terkoyak. Nawawi bin Zaenal Mansur (45) kini tak bisa lagi nyekar di makam orang tua seperti dulu. Di hari menjelang puasa yang sumuk itu, Nawawi bersama anak dan istrinya duduk di atas pepuingan. Ia khusyuk berdoa. Matanya menerawang ke arah sebuah kuburan umum Dusun Renokenongo. Cuma terlihat pucuk kamboja yang mengering. Kuburan itu telah lenyap.
Doa khusus dia tujukan pada Zaenal Mansur, sang ayah, seorang pejuang kemerdekaan. Kali ini dia tak membawa bunga dan tak bisa menaburnya di atas kubur sang ayah. Tahun lalu, dia masih bisa ke kuburan bapaknya karena air asin dan lumpur mengering. Ketika itu dia lihat bendera merah putih dari seng di atas kuburan sudah mulai peot.
Menjelang puasa tahun ini, Nawawi tak lagi bisa nyekar. Nawawi tak habis pikir dengan Lapindo dan pemerintah yang lamban menangani soal lumpur Lapindo ini. Sudah dua tahun ini dia hidup berpindah-pindah.
Tak hanya kuburan Dusun Renokenongo yang tenggelam. Kuburan Dusun Sengon, masih dalam Desa Renokenongo, juga terendam di tengah lumpur di dalam tanggul Lapindo. Penduduknya tak bisa lagi nyekar di kubur keluarga mereka. Mereka hanya mendoakan dari atas tanggul menghadap kuburan yang juga ditandai gerumbul kamboja yang mengering.
Muhammad Yunus (40 tahun) adalah salah satu warga Sengon yang keluarganya dimakamkan di kuburan umum Dusun Sengon. Sore itu Yunus tak bisa nyekar dan hanya mendoakan arwah keluarga dari atas tanggul. Dia menangis melihat kubur orang-orang yang dicintainya tenggelam oleh lumpur.
Soal kuburan yang tenggelam, menurut Yunus, tak ada bahasan ganti rugi sama sekali. Penduduk sudah pusing memikirkan tuntutan dasar mereka yang tak jelas kapan dilunasi. Yunus ingin kuburan yang sudah tenggelam ini dipindahkan ke tempat lain supaya dia bisa berziarah. “Warga sebenarnya ingin makam dipindah, kersane saget ziarah, supaya bisa ziarah.”
Soal kuburan ini tak hanya soal ziarah dan tradisi yang hilang. Namun juga soal bagaimana kalau warga dari kampung-kampung yang tenggelam ini mati. Pertanyaannya, mau dimakamkan di mana mereka kalau meninggal? Untuk warga Renokenongo yang kembali ke desa karena kontrakannya habis dan mati mereka akan dikuburkan di makam tetangga desa mereka, Glagaharum.
Selama dua tahun pasca luapan lumpur, sudah 30 orang warga Renokenongo di pengungsian Pasar Baru Porong yang meninggal. Mereka nebeng makam di Desa Juwet Kenongo.
“Mereka dikumpulkan di pojok, tak boleh milih tempat sembarangan,” tutur Nizar warga Renokenongo yang mengungsi di Pasar Porong Baru.
Selain dua kuburan di Desa Renokenongo, kuburan-kuburan di Desa Siring, Kedungbendo, Mindi, Jatirejo Timur, Jatianom juga ditenggelamkan lumpur Lapindo. Jelang Ramadlan warga Mindi melakukan aksi nyekar di tanggul dan mendoakan leluhur mereka di sana.
“Di Jatirejo ada dua kuburan satu di Jatirejo Timur dan Barat. Yang di Jatirejo Timur sudah tenggelam dan yang di Barat masih,” tutur Ahmad Novik (29 tahun) warga Jatirejo.
Sementara penduduk Besuki yang setengah kampungnya ditenggelamkan lumpur masih beruntung karena kuburan mereka masih bisa digunakan. Dulu sempat tergenang lumpur tapi kini sudah kering. Meski kuburan itu dilapisi lumpur namun penduduk masih bisa menggunakannya. Sore sehari menjelang Ramadlan, penduduk Besuki memadati kuburan berlumpur itu untuk menjalankan tradisi nyekar dan mendoakan arwah keluarga mereka.
Suroso adalah salah satu warga Besuki yang nyekar sore itu. Tak hanya menjelang Ramadlan, biasanya, Suroso ziarah ke makam orang tuanya setiap malam Jumat.
“Ini sudah menjadi adat kebiasaan yang diharuskan menjelang puasa dan Idul Fitri,” tutur Suroso. Dan berapa besar kerugian atas hilangnya tradisi ini? Lapindo tak bicara. Pemerintah pun bungkam. [ba/re/mam]

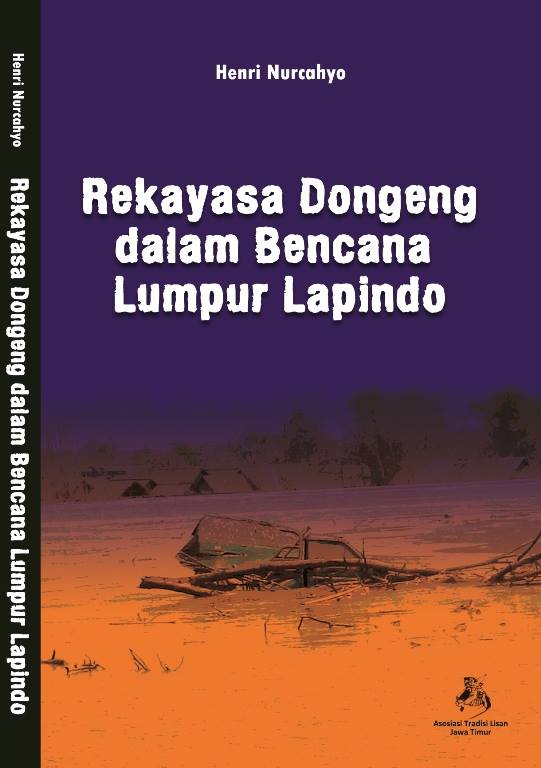
 Judul Buku : Rekayasa Dongeng dalam Bencana Lumpur Lapindo
Judul Buku : Rekayasa Dongeng dalam Bencana Lumpur Lapindo