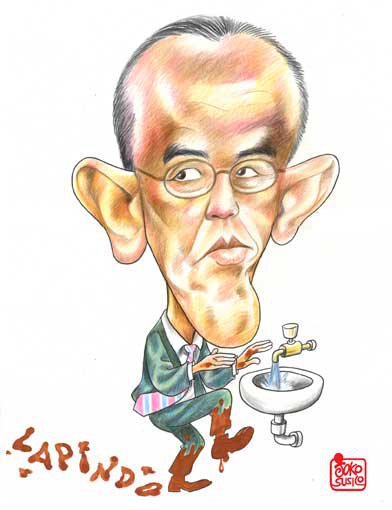Versi PDF [unduh]
Oleh Anton Novenanto
RENCANA PEMERINTAH MENALANGI hutang Lapindo pada korban lumpur di Sidoarjo senilai Rp 781 milyar menggunakan dana taktis APBN 2015 patut didiskusikan secara kritis.
Berangkat dari perspektif ‘korban’, mayoritas publik menilai pelunasan hutang Lapindo tersebut merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat korban sudah terlalu menunggu dalam ketidakpastian. Dana talangan adalah solusi darurat yang harus diambil oleh pemerintah untuk memberi kepastian pada para korban.
Hanya sedikit dari publik yang tahu bahwa dana talangan hanya menyentuh satu kelompok korban Lapindo, kelompok cash and carry. Padahal, masih banyak kelompok korban lain yang tidak tersentuh oleh dana talangan dari pemerintah tersebut dan setiap kelompok itu menghadapi beragam masalah yang bisa jadi berbeda satu sama lain.
Pada saat yang bersamaan, terdapat sekelompok orang yang berangkat dari perspektif ‘korporasi’ mempertanyakan secara kritis rencana pemerintah tersebut. Pemberian dana talangan merupakan strategi ekonomi-politik yang hanya menguntungkan konglomerasi besar yang sedang terlilit masalah finansial. Dalam kasus Lapindo, korporasi itu adalah Grup Bakrie. Logikanya sederhana: bukannya menghukum, negara justru membantu si pelaku kejahatan.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, dana talangan berujung pada praktik koruptif para penyedia dan penerima dana talangan, seperti kasus BLBI dan kasus Bank Century. Dana talangan itu tidak pernah kembali ke kas negara. Kritik dari kelompok ini dapat dirangkum dalam sebuah pertanyaan kritis: apakah pemerintah juga akan menyediakan dana talangan bagi korban Lapindo yang terlilit hutang akibat tertundanya pembayaran hak mereka selama bertahun-tahun?
Terlepas dari pro-kontra terhadap rencana dana talangan untuk kasus Lapindo, yang tak kalah menarik perhatian adalah rencana pemerintah untuk menyita aset perusahaan bila dana tersebut tidak dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Rencana ini mendorong penulis untuk meninjau kembali kasus Lapindo menggunakan perspektif ‘objek’ – tanah yang menjadi medium relasi kuasa antara para agen yang terlibat di dalamnya.
***
KOMPLEKSITAS PENANGANAN KASUS Lapindo bermula sejak penandatanganan Perpres 14/2007 tentang BPLS pada 8 April 2007. Salah satu hal prinsipil dalam Perpres itu adalah tentang bagaimana pemerintah menyederhanakan konsep ‘ganti-rugi’ menjadi praktik ‘jual-beli’.
Secara sosiologis, terdapat perbedaan hakiki dalam relasi sosial yang disebabkan oleh masing-masing konsep itu. Dalam logika ‘ganti-rugi’ relasi sosial yang terjadi adalah antara korban dan pelaku dengan mengandaikan otoritas superior (penegak hukum, negara, juri) yang mengawasi proses tersebut. Sementara itu, dalam proses ‘jual-beli’ relasi sosial yang terjadi adalah antara penjual dan pembeli, dalam hal ini warga sebagai penjual dan Lapindo sebagai pembeli. Objek yang diperjualbelikan adalah tanah dan bangunan dalam peta area terdampak (PAT) tertanggal 22 Maret 2007.
Sekalipun nilai tukar dari objek yang sedang dipertukarkan sama besarnya, hakikat pertukarannya tidak pernah sama. Dalam proses ‘ganti-rugi’, pelaku mengganti kerugian yang diderita oleh korban tanpa ada peralihan kepemilikan apapun. Sementara itu, ‘jual-beli’ mengutamakan peralihan kepemilikan dari pembeli ke penjual. Dan justru di sinilah letak masalahnya ketika objek yang sedang diperjualbelikan, salah satunya, adalah tanah.
Mengacu pada peraturan yang ada, hanya ada dua subjek hukum yang boleh memperoleh ‘hak milik’ atas tanah, yaitu warga negara Indonesia (pribadi) dan badan hukum tertentu (UU Agraria No. 5/1960, Pasal 26 Ayat 2). Termasuk dalam badan hukum adalah bank negara, koperasi pertanian, organisasi keagamaan dan badan sosial (PP No. 38/1963, Pasal 1). Mengikuti UU Agraria 5/1960, transaksi tanah pada badan hukum selain itu, seperti Lapindo atau Minarak, akan batal secara hukum dan segala pembayaran yang telah dilakukan tak dapat dituntut kembali dan status tanah berubah menjadi ‘tanah negara’ (Pasal 27a).
Mekanisme jual-beli antara warga-korban dan Lapindo telah diatur dalam Surat Kepala BPN tanggal 24 Maret 2008. Dan, menurut Perpres 48/2008, tanah dalam peta area terdampak statusnya beralih menjadi ‘barang milik negara’. Jika betul demikian, maka pertanyaan kritis kita adalah: bagaimana mungkin negara menyita aset yang statusnya sudah pasti bakal menjadi ‘tanah negara’?
Berdasarkan penelusuran singkat tersebut, penulis berpendapat bahwa rencana ‘dana talangan’ dan ‘sita aset’ Lapindo merupakan bukti dari kedangkalan pemerintah memahami lansekap-bencana lumpur Lapindo. Pemerintah, dan publik umum (termasuk media massa) telah secara sempit memahami kasus Lapindo sebatas ‘ganti-rugi’ (itupun sebenarnya sudah direduksi menjadi ‘jual-beli’) apalagi untuk sampai pada persoalan pemulihan sosial-ekologis.
***
BILA KITA MAU secara jeli memahami kasus Lapindo, kita akan menjumpai pelbagai fakta yang menunjukkan bahwa sisa hutang Lapindo melampaui Rp781 milyar. Lapindo juga masih berhutang pada para pengusaha melalui mekanisme B-to-B yang jumlahnya mencapai senilai Rp514 milyar. Selain itu, masih banyak korban dari kelompok cash and resettlement, misalnya, yang belum mendapatkan kepastian kapan mereka akan mendapatkan sertifikat atas tanah dan rumah baru di Kahuripan Nirvana Village (KNV). Bagi kelompok ini, selama Lapindo belum menyerahkan sertifikat tersebut proses transaksi belumlah selesai dan Lapindo masih berhutang pada mereka.
Selain persoalan ekonomi, dampak dan resiko sosial-ekologis juga kerap luput dari amatan publik. Pembuangan lumpur ke Selat Madura menyebabkan pendangkalan dan pencemaran di sepanjang DAS Porong yang berujung pada menurunnya produksi perikanan pantai timur Sidoarjo. Sampai kini belum terdengar program jangka panjang untuk melakukan normalisasi DAS Porong. Alih fungsi lahan akibat proyek relokasi jalan raya, jalan tol, dan juga permukiman kembali korban Lapindo merupakan sumber bagi meluasnya persoalan pada jaring sosial-ekologis yang lain.
Dana talangan memang penting dan mendesak bagi para korban, namun rencana itu baru menyentuh sebagian dari kasus Lapindo. Dana itu hanyalah solusi darurat dan parsial karena diperuntukkan bagi sebagian korban dari kelompok cash and carry. Tentunya, masih banyak persoalan lain yang memunculkan dan dimunculkan oleh lumpur Lapindo yang membutuhkan perhatian dan tindakan konkret dari pemerintah.
Pemerintah tidak pernah tegas, misalnya, untuk mengusut pemberian izin pada Lapindo untuk melakukan pemboran Sumur Banjar Panji 1, dan juga sumur-sumur yang lain, di kawasan padat huni. Pemerintah juga tidak pernah tegas untuk menindak Lapindo yang jelas-jelas melanggar Perpres 14/2007 yang mewajibkan Lapindo untuk melunasi pembayaran pada korban sebelum dua tahun setelah uang muka dibayarkan (Pasal 14 Ayat 2). Alih-alih menghukum, pemerintah justru mereduksi tanggung jawab Lapindo secara bertahap.
***
SEBAGAI BAGIAN DARI publik kritis, kita seharusnya terus mempertanyakan ‘kemauan politik’ pemerintah untuk secara serius memahami kompleksitas kasus Lapindo dan mengusutnya sampai tuntas. Karena bila bukan pemerintah, lalu otorita politik apa lagi yang bisa?
Kasus Lapindo akan selalu menjadi uji kasus bagi siapapun yang duduk di kursi kekuasaan, termasuk Presiden Joko Widodo. Tentunya, publik sangat berharap agar dalam masa pemerintahan saat ini keadilan betul-betul ditegakkan. Kini saatnya menenggelamkan sang raksasa jahat dalam lumpur Lapindo, bukannya justru melindungi dan ikut tenggelam bersamanya.
(bersambung: Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Etika)
Heidelberg, 11 Januari 2015
Penulis adalah dosen pada Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya. Mendalami kasus Lapindo sejak 2008 hingga kini.
Catatan penulis: beberapa pendapat dalam artikel ini pernah disampaikan ke beberapa media cetak tanpa ada kejelasan.
Versi PDF [unduh]